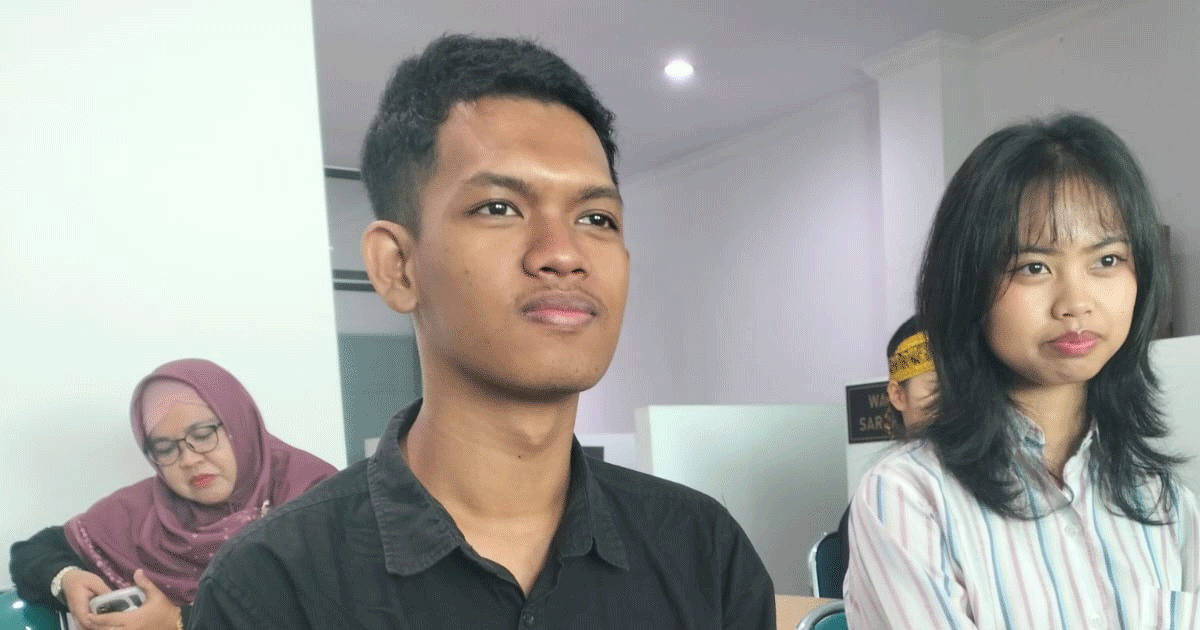Dampak Positif Koperasi Desa Merah Putih Program Presiden Prabowo Subianto

INDOPOSCO.ID – Indonesia sebagai negara berkembang dengan populasi besar dan wilayah geografis yang luas menghadapi tantangan struktural dalam mencapai pemerataan ekonomi. (Supriatin dyah 2022) Salah satu ciri khas perekonomian Indonesia adalah dominasi sektor informal dan ketergantungan yang tinggi terhadap aktivitas ekonomi pedesaan. Ketimpangan distribusi pendapatan, keterbatasan akses keuangan, dan lemahnya posisi tawar petani serta pelaku usaha mikro menjadi masalah laten yang belum terselesaikan secara menyeluruh.
Dalam konteks ini, kebutuhan akan pendekatan pembangunan yang berbasis komunitas dan inklusif menjadi semakin mendesak, terutama ketika sistem keuangan konvensional sering kali gagal menjangkau akar rumput secara adil dan berkelanjutan (M 2009).
Menurut (Firdausy et al. 2019) Pemerintah menargetkan pendirian koperasi ini di 70 ribu hingga 80 ribu desa di seluruh Indonesia, menjadikannya salah satu kebijakan revitalisasi ekonomi desa paling ambisius dalam sejarah pembangunan nasional. Koperasi ini diharapkan menjadi simpul kegiatan ekonomi lokal, mulai dari penyimpanan hasil pertanian, distribusi pangan, pengelolaan modal usaha, hingga penguatan sistem keuangan mikro berbasis komunitas.
Program Koperasi Desa Merah Putih akan didukung oleh optimalisasi dana desa dan pembiayaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dengan skema cicilan selama tiga hingga lima tahun dan nilai investasi per desa mencapai Rp3–5 miliar (Alfitria Nefi, n.d.). Pengembangan koperasi akan dilakukan melalui tiga pendekatan utama: membentuk koperasi baru, merevitalisasi koperasi lama, dan memperkuat koperasi yang sudah berjalan.
Sekitar 64 ribu kelompok tani telah menyatakan kesiapannya untuk bermigrasi ke sistem koperasi ini. (Sofyan 2017)
Kebijakan ini tidak hanya merupakan langkah ekonomi, tetapi juga simbol perlawanan terhadap dominasi sistem keuangan top-down yang cenderung terpusat
dan eksklusif (Díaz 2021). Dalam konteks globalisasi keuangan, di mana kontrol ekonomi semakin berpindah ke entitas besar dan terpusat, inisiatif koperasi desa menjadi bentuk nyata pembangunan alternatif berbasis rakyat.
Dengan memadukan pembiayaan publik, partisipasi masyarakat, dan orientasi kewirausahaan lokal, Kop Des Merah Putih menawarkan potensi besar untuk membangun sistem keuangan yang tangguh, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan zaman (Hakim, Lukmanul; Svinarky 2022).
Esai ini bertujuan untuk mengulas secara mendalam dampak positif Koperasi Desa Merah Putih dalam konteks penguatan stabilitas keuangan lokal, pembangunan desa berkelanjutan, serta ketahanan ekonomi mikro.
Lebih dari itu, tulisan ini juga akan membahas bagaimana kebijakan tersebut merefleksikan arah baru pembangunan nasional di tengah tantangan global, serta sejauh mana ia dapat menjadi model kebijakan yang menjawab ketimpangan struktural dan keterbatasan sistem keuangan konvensional.
Landasan Teoretis
Menurut (Alderson, J. Charles & Wall 1992) Memahami secara menyeluruh dampak program Koperasi terhadap pembangunan ekonomi lokal dan stabilitas keuangan mikro di tengah tantangan globalisasi, diperlukan fondasi teoritis yang kuat dari berbagai pendekatan dalam ilmu keuangan dan pembangunan.
Beberapa teori utama yang digunakan dalam esai ini mencakup teori intermediasi keuangan, keuangan berbasis komunitas, pembangunan inklusif, dan kemandirian pangan.
Menurut (Fahmi 2014) Teori Intermediasi Keuangan, menyatakan bahwa lembaga keuangan non-bank seperti koperasi berperan penting dalam mengisi kekosongan sistem keuangan formal, khususnya di wilayah pedesaan atau yang secara geografis dan ekonomi terpinggirkan.
Dalam sistem keuangan modern yang cenderung berpusat pada kota besar dan kelompok ekonomi menengah ke atas, peran koperasi menjadi krusial sebagai agen intermediasi yang mampu menjangkau masyarakat miskin, petani, dan pelaku usaha mikro. Melalui fungsi penghimpunan dana, penyaluran kredit, dan pendampingan ekonomi, koperasi dapat menjadi jembatan antara kebutuhan riil masyarakat desa dengan sistem keuangan nasional. (Siti Indah Purwaning Yuwana 2021).
Kedua, Teori Keuangan Berbasis Komunitas – Community-Based Finance Theory sebagaimana (Sonita 2019), menekankan bahwa lembaga keuangan lokal yang dibangun oleh dan untuk masyarakat memiliki keunggulan dalam hal keterjangkauan, tingkat kepercayaan sosial, dan fleksibilitas dalam merespons kebutuhan lokal.
Hal ini relevan dalam konteks Kop Des Merah Putih, di mana pendekatan bottom-up menjadi prinsip utama dalam perencanaan dan pelaksanaan koperasi. Menurut (Baihaqi 2018) Kepercayaan sosial yang tinggi antaranggota, kedekatan geografis, serta pemahaman terhadap siklus pertanian atau ekonomi lokal membuat koperasi lebih tangguh dalam menghadapi risiko gagal bayar maupun ketidakpastian pasar.
Ketiga, menurut (Setiawan 2024) Teori Pembangunan Inklusif (Inclusive Growth) sebagaimana dirumuskan oleh OECD (2012), menggarisbawahi pentingnya partisipasi luas masyarakat dalam proses pertumbuhan ekonomi agar manfaatnya tersebar secara adil. Pendekatan ini mengutamakan pemerataan peluang, perlindungan kelompok rentan, serta pembangunan ekonomi lokal sebagai basis dari pertumbuhan yang berkelanjutan.
Dalam kerangka ini, koperasi desa dipandang sebagai instrumen kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada indikator pengurangan ketimpangan (Goal 10), pemberdayaan ekonomi (Goal 8), dan penguatan kelembagaan lokal (Goal 16).(Natalia and Maulidya 2023).
Keempat, menurut (Akbar 2018) Teori Pembangunan Partisipatif yang memperkuat argumen bahwa pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama, bukan sekadar sebagai objek penerima bantuan.
Dalam konteks ini, program Kop Des Merah Putih mengadopsi pendekatan partisipatif melalui pembentukan koperasi dari kelompok tani dan komunitas lokal yang sudah eksis (Suwandi and Rostyaningsih 2012). Strategi ini tidak hanya meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap koperasi, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan ekonomi di tingkat desa.
Kelima, menurut (Hakim and Irawan 2019)Teori Kemandirian Pangan memberikan kerangka bahwa pembangunan distribusi pangan yang adil dan efisien di tingkat lokal sangat penting untuk mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi pasar global.
Negara-negara berkembang disarankan untuk memperkuat sistem produksi dan logistik pangan lokal agar ketahanan pangan nasional dapat dicapai (Azahari 2008). Dengan menjadikan koperasi sebagai simpul penyimpanan, distribusi, dan pemasaran hasil pertanian, program Kop Des Merah Putih berpotensi memperpendek rantai distribusi dan meningkatkan efisiensi ekonomi desa.
Seluruh pendekatan teoritis ini menjadi lensa analisis dalam menilai efektivitas dan potensi jangka panjang Kop Des Merah Putih. Lebih jauh, program ini juga dapat dibaca sebagai bentuk resistensi terhadap arus globalisasi keuangan yang kerap kali mengabaikan kebutuhan ekonomi akar rumput.
Dengan mendesain koperasi sebagai institusi keuangan berbasis komunitas yang kuat, kebijakan ini mampu menciptakan ruang baru bagi demokratisasi ekonomi dan penyusunan ulang struktur ekonomi nasional yang lebih adil dan berkelanjutan.
Bagian Utama Analisis
Menurut (Alfitria Nefi, n.d.) Program Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai upaya struktural untuk mengatasi ketimpangan pembangunan dan keterbatasan akses keuangan di pedesaan Indonesia. Dengan cakupan lebih dari 74.000 desa, program ini mengusung model koperasi terintegrasi yang didukung penuh oleh negara dan diperkuat melalui pelatihan manajerial serta pendampingan teknis.
Tiga pilar utama yang menjadi fondasinya adalah penyediaan akses permodalan mikro tanpa bunga tinggi, pendampingan usaha dan literasi keuangan, serta penyerapan produk pertanian dan lokal melalui sistem distribusi koperasi.
Program ini secara ideologis merupakan antitesis dari dominasi model pembiayaan konvensional dan fintech global yang seringkali menjerat masyarakat desa dalam lingkaran utang berbunga tinggi. Lebih dari itu, koperasi desa telah lama terbukti efektif dalam memperkuat ekonomi mikro, sebagaimana dicatat Birchall (2004) di Afrika dan Asia.
Di Indonesia, keberhasilan koperasi pilot di Trenggalek, Jawa Timur, yang meningkatkan pendapatan UMKM lokal hingga 45% dalam enam bulan, menjadi bukti nyata kekuatan ekonomi komunitas dalam memutus ketergantungan terhadap rentenir atau pinjaman online ilegal.
Keunggulan strategis lain dari program ini adalah kemampuannya menghubungkan sistem keuangan informal desa ke sistem keuangan nasional melalui integrasi teknologi digital seperti QRIS dan BI-FAST (Marginingsih 2023). Transformasi ini menjadikan koperasi sebagai entitas keuangan formal yang tetap menjaga nilai gotong royong, serupa dengan praktik sukses di Kenya dan Filipina.
Kop Des Merah Putih tidak hanya mengejar inklusi keuangan, tetapi juga memadukan praktik global dengan kearifan lokal. Di sisi lain, koperasi juga terbukti memperkuat ketahanan sosial dan pembangunan inklusif. Dengan pendekatan partisipatif, masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan ekonomi, memperkuat modal sosial, dan memperkecil ketimpangan antarwilayah.
Data Bappenas (2025) menunjukkan bahwa daerah yang mengadopsi koperasi desa mengalami penurunan rasio Gini sebesar 0,02 poin dalam satu tahun, mempertegas kontribusinya terhadap agenda SDGs, terutama pengentasan kemiskinan, pekerjaan
Dalam tataran global, koperasi desa menjadi alternatif terhadap sistem keuangan internasional yang didominasi institusi multinasional seperti IMF dan Bank Dunia. Stiglitz (2002) telah mengkritik keras liberalisasi keuangan global yang memperdalam jurang sosial.
Program Kop Des Merah Putih dapat dibaca sebagai resistensi terhadap logika keuntungan pasar global, sebagaimana juga terlihat pada koperasi kredit di Bolivia dan Brasil. Dukungan negara melalui dana desa, regulasi, dan pelatihan menjadikan model Indonesia unik dan inovatif.
Program ini juga berkontribusi terhadap revitalisasi ekonomi desa dengan menjadikan koperasi sebagai pusat produksi, pengolahan, dan distribusi. Dengan memangkas rantai distribusi yang panjang dan inefisien, koperasi mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal dan posisi tawar petani.
Strategi pendanaan melalui integrasi dana desa sebesar Rp1 miliar per desa per tahun selama lima tahun menegaskan komitmen negara. Ditambah dukungan Himbara melalui skema kredit lunak, koperasi diyakini lebih transparan dan akuntabel dibanding proyek pembangunan konvensional.
Di sektor pangan, koperasi berperan penting sebagai off-taker hasil pertanian, menyederhanakan logistik, menstabilkan harga, dan meningkatkan daya saing. Dengan dukungan digitalisasi, koperasi juga dapat berfungsi sebagai pusat data komoditas yang memperpendek jarak antara produsen dan konsumen.
Lebih jauh, koperasi desa juga memperkuat struktur sosial-ekonomi melalui pelatihan keuangan, manajemen kolektif, dan demokratisasi ekonomi. Proses ini melahirkan wirausahawan baru di sektor pengolahan hasil tani, industri rumah tangga, dan jasa lokal, menjadi katalis bagi ekonomi kreatif desa.
Dalam skala internasional, program ini menawarkan model keuangan mikro alternatif yang tidak hanya meniru keberhasilan seperti SHG India, Grameen Bank Bangladesh, atau SACCOs Kenya, tetapi melampauinya melalui dukungan negara secara komprehensif.
Dengan pendekatan yang inklusif dan tahan terhadap guncangan global, koperasi desa Indonesia menjadi contoh baru bagi negara-negara berkembang dalam membangun sistem keuangan mikro yang mandiri dan berkeadilan.
Kesimpulan
Program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar inisiatif pembangunan ekonomi berbasis desa, melainkan representasi dari perubahan paradigma sistem keuangan nasional yang bergerak dari akar rumput. Dengan mengedepankan prinsip gotong royong, kedaulatan
ekonomi lokal, dan akses inklusif terhadap pembiayaan, program ini menghadirkan model keuangan mikro yang berkeadilan di tengah dominasi sistem keuangan global yang cenderung eksklusif dan sentralistik. Koperasi desa tidak hanya menjadi alat pemberdayaan ekonomi, tetapi juga sarana demokratisasi keuangan yang memperkuat struktur sosial masyarakat.
Skalanya yang menyasar seluruh desa di Indonesia menjadikan program ini sebagai salah satu transformasi ekonomi paling ambisius dalam sejarah modern bangsa.
Melalui optimalisasi dana desa, pemangkasan rantai distribusi pangan, dan penguatan peran petani serta pelaku UMKM, program ini menunjukkan bahwa pembangunan dari bawah tidak hanya mungkin, tetapi juga strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan ketahanan ekonomi nasional.
Jika dijalankan dengan tata kelola yang baik dan pengawasan publik yang kuat, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi model inspiratif, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara berkembang lainnya dalam mencari jalur pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. (srv)
Penulis :
Wahyudi Setiawan,
Pemerhati Ekonomi Indonesia dan Mahasiswa S3 di SKSG Universitas Indonesia
Daftar Pustaka
Akbar, Idil. 2018. “Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Lokal: Studi Di Kota Bandung.” Jurnal Reformasi Administrasi 5 (2): 101–8.
Alderson, J. Charles & Wall, Dianne. 1992. “Peran Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia.” Japanese Society of Biofeedback Research 19:709–15.
https://doi.org/10.20595/jjbf.19.0_3.
Alfitria Nefi. n.d. “No Title.” Tempo. https://www.tempo.co/ekonomi/apbn-jadi- penjamin-pinjaman-bank-himbara-untuk-koperasi-desa-merah-putih- 1324529.
Azahari, Delima Hasri. 2008. “Disampaikan Dan Diingatkan Oleh Presiden RI Pertama , Ir Soekarno Yang Bangsa . Meskipun Disampaikan Beberapa Puluh Tahun Yang Lalu , Namun Persoalan Nasional . Fakta Sejarah Telah Membuktikan Bahwa Permasalahan Pangan Adalah Didasarkan Atas Peran Strateg.” Analisis Kebijakan Pertania 6 (70): 174–95.
Baihaqi, Jadzil. 2018. “Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia.” TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law 1 (2): 116. https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4979.
Bappenas. (2025). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025– 2029. Jakarta: Bappenas.
Bappenas. (2025). RPJMN 2025–2029: Strategi Pembangunan Desa dan Ketahanan Pangan Nasional. Jakarta: Kementerian PPN.
Birchall, J. (2004). Cooperatives and the Millennium Development Goals. International Labour Organization.
Chambers, R. (1983). Rural Development: Putting the Last First. London: Longman.
Díaz, Francisco. 2021. New Normal. Arq. Vol. 2021. https://doi.org/10.4067/S0717-69962021000100010.
Fahmi, Irham. 2014. “Manajemen Keuangan Perusahaan Dan Pasar Modal.” Jamal Wiwoho, Peran LKB Dan LKBB 43 (1): 87–97.
FAO. (2017). The Future of Food and Agriculture: Trends and Challenges. Rome: United Nations.
Firdausy, Carunia Mulya, Achmad Suryana, Riant Nugroho, and Y.B. Suhartoko. 2019. “Revolusi Industri 4.0 Dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan.” Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. 2019.
Gurley, J. G., & Shaw, E. S. (1960). Money in a Theory of Finance. Brookings Instituion.
Gurley, J. G., & Shaw, E. S. (1960). Money in a Theory of Finance. Brookings Institution.
Hakim, Lathif, and Indra Ade Irawan. 2019. “Strategi Membangun Kemandirian Pangan Nasional Dengan Meminimalisir Impor Untuk Kesejahteraan Rakyat.” Indikator: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis 3 (3): 209–22.
https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/indikator/article/view/7459.
Hakim, Lukmanul; Svinarky, Irene; dkk. 2022. “BUM DESA SEBAGAI KEKUATAN EKONOMI BARU (Sebuah Gagasan Untuk Desa Di Indonesia).” Penerbit Lakeisha, no. February, 828.
https://www.researchgate.net/profile/Fx-Anjar- Laksono/publication/358468492_BUM_desa_sebagai_kekuatan_ekonomi_baru_sebuah_gagasan_untuk_desa_di_Indonesia/links/6203d41bc83d2b75dff d64b3/BUM-desa-sebagai-kekuatan-ekonomi-baru-sebuah-gagasan-untuk- desa-di-In.
Kementerian Koperasi dan UKM. (2024). Laporan Implementasi Koperasi Desa Merah Putih. Jakarta: Kemenkop UKM.
Kementerian Koperasi dan UKM. (2025). Strategi Nasional Penguatan Koperasi Desa. Jakarta. Ledgerwood, J. (1999). Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective. World Bank.
M, Fani Cahyandito, Erie Febrian, dkk. 2009. Komunikasi_Pembangunan_Berkelanjutan_Sus. https://pustaka.unpad.ac.id/wp- content/uploads/2009/06/proceding_isei_menado_komunikasi_pemb_kembe rlanjutan_fani.pdf.
Marginingsih, Ratnawaty. 2023. “BI-FAST Sebagai Sistem Pembayaran Dalam Mendukung Akselerasi Digitalisasi Ekonomi Dan Keuangan Nasional.” Moneter – Jurnal Akuntansi Dan Keuangan 10 (1): 18–26.
https://doi.org/10.31294/moneter.v10i1.15356.
Natalia, Angga, and Erine Nur Maulidya. 2023. “Aktualisasi Empat Pilar Sustainable Development Goals (SDGs) Di Perdesaan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.” JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 8 (1): 21–41.
https://doi.org/10.14710/jiip.v8i1.16513.
OECD. (2012). Inclusive Growth Framework. Paris: OECD Publishing.
OECD. (2012). Promoting Inclusive Growth: Challenges and Policies. OECD Publishing.
Setiawan, Avi Budi. 2024. “Pembangunan Indonesia Pembangunan Inklusif Dan Industrialisasi Di Indonesia : Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pembangunan Inklusif Dan Industrialisasi Di Indonesia : Dampaknya Terhadap” 24 (2).
https://doi.org/10.21002/jepi.2024.10.
Siti Indah Purwaning Yuwana. 2021. “Strategi Pengembangan Modal Koperasi Simpan Pinjam Melalui Bantuan LPDB.” Jurnal Lemhannas RI 9 (3): 35–48.
https://doi.org/10.55960/jlri.v9i3.400.
Sofyan, Syaakir. 2017. “Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia.” Jurnal Bilancia 11 (1): 33–59.
file:///C:/Users/Asus/Downloads/298-Article Text-380-1-10-20180728-3.pdf.
Sonita, Era. 2019. “Sistem Pembiayaan Sosial Berbasis Komunitas.” Al-Masraf : Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan 4 (2): 235.
https://doi.org/10.15548/al-masraf.v4i2.270.
Stiglitz, J. (2002). Globalization and Its Discontents. W.W. Norton & Company.
Stiglitz, J. E. (2002). Globalization and Its Discontents. W.W. Norton & Company.
Supriatin dyah. 2022. “BUKU PEREKONOMIAN INDONESIA Dengan Cover Apit.Pdf.” Tiga Cakrawala.
Suwandi, and Dewi Rostyaningsih. 2012. “Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.” Journal of Public Policy and Management Review 1 (2): 261–70.